
Oleh Ramli Lahaping
 Perputaran waktu terasa makin melambat. Aku jadi tidak sabar untuk sampai pada momen beberapa jam ke depan. Itu karena anakku akan datang dari negara seberang, beserta menantu dan cucuku. Mereka akan sampai sebelum malam, dengan membawa segenap cinta yang sekian lama kurindukan.
Perputaran waktu terasa makin melambat. Aku jadi tidak sabar untuk sampai pada momen beberapa jam ke depan. Itu karena anakku akan datang dari negara seberang, beserta menantu dan cucuku. Mereka akan sampai sebelum malam, dengan membawa segenap cinta yang sekian lama kurindukan.
Aku memang telah terpisah lama dengan anakku, juga keluarga kecilnya. Kami baru akan bertemu kalau ia punya waktu libur kerja yang panjang. Pasalnya, ia bekerja di sebuah perusahaan otomotif di negara kediamannya. Sebuah perusahaan yang memiliki disiplin kerja yang ketat, yang menilai bahwa melalaikan atau meninggalkan tugas berarti mengundurkan diri.
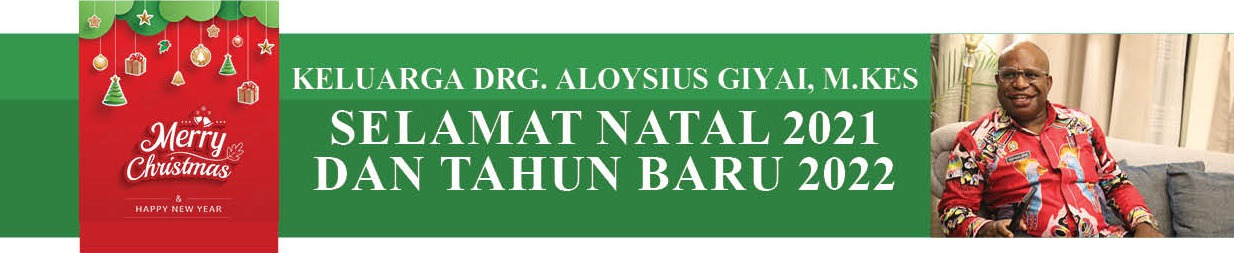 Tetapi sekian lama terpisah untuk kesekian kalinya, membuatku terbiasa hidup tanpa siapa-siapa. Apalagi, aku memang seharusnya merelakan anakku untuk pergi dan tinggal di tempat yang jauh demi kemajuan hidupnya. Terlebih, keberadaannya di negara seberang juga berarti bahwa ia berada di negara ayah kandungnya sendiri, tanpa sepengetahuannya.
Tetapi sekian lama terpisah untuk kesekian kalinya, membuatku terbiasa hidup tanpa siapa-siapa. Apalagi, aku memang seharusnya merelakan anakku untuk pergi dan tinggal di tempat yang jauh demi kemajuan hidupnya. Terlebih, keberadaannya di negara seberang juga berarti bahwa ia berada di negara ayah kandungnya sendiri, tanpa sepengetahuannya.
Sampai kini, ia memang tidak tahu siapa lelaki yang menanamkan benih dirinya di rahimku dahulu. Yang ia tahu kemudian, aku bersuamikan seorang lelaki pribumi, dan ia menerima saja veteran pejuang kemerdekaan itu sebagai ayahnya. Ia sama sekali tak menaruh curiga perihal kenapa rupa wajahnya dan warna kulitnya berbeda dengan orang-orang di negara ini.
Perkara sengkarut silsilahnya itu, terjadi karena perang penjajahan yang membunuh kemanusiaan. Kala itu, aku jatuh hati kepada seorang tentara dari negara seberang tersebut, yang turut titah pemerintahnya untuk menjajah negaraku. Ia lalu ditugaskan untuk mengawasi pembangunan jalan di kampungku, dan ia melakukannya tanpa kekerasan, sehingga aku jadi terkesan.
 Tanpa kuduga, lelaki itu membalas perasaanku. Demi cinta, ia tak mempersoalkan perbedaan di antara kami. Ia kukuh menantang bahaya di tengah ketegangan dan gejolak penjajahan versus perlawanan, sebagaimana aku, demi masa depan kami. Sampai akhirnya, kami memadu kasih rahasia terlalu jauh, hingga kami melakukan hubungan badan yang tak semestinya.
Tanpa kuduga, lelaki itu membalas perasaanku. Demi cinta, ia tak mempersoalkan perbedaan di antara kami. Ia kukuh menantang bahaya di tengah ketegangan dan gejolak penjajahan versus perlawanan, sebagaimana aku, demi masa depan kami. Sampai akhirnya, kami memadu kasih rahasia terlalu jauh, hingga kami melakukan hubungan badan yang tak semestinya.
“Aku mencintaimu, dan aku ingin bersamamu selamannya,” tuturnya, di malam yang remang itu, di bawah bulan purnama yang cerah, di sebuah gubuk yang jauh dari keramaian. Ia mengucapkannya dengan setengah berbisik, dengan pelafalan kata yang terbata-bata, sebab ia belumlah fasih berbahasa dengan bahasaku.
“Tetapi apakah itu mungkin? Kau tahu sendiri kalau keadaan membuat kita tidak mungkin bersama, kan?” tanyaku, kalut.
Ia lantas mendengkus cemas, sembari membelai-belai rambutku. Ia seolah kelimpungan juga mememikirkan kelanjutan hubungan kami. “Semoga saja pertikaian antarbangsa segera berakhir, sehingga kita bisa terus hidup bersama, tanpa mengkhawatirkan apa-apa,” harapnya, dengan raut penuh ketulusan.
Aku hanya mengangguk dan menyemogakan harapan yang sama.
Pada waktu kemudian, perang dunia pun berakhir. Negaranya menderita kekalahan, dan ia harus menyingkir dari tanah airku yang kembali dikuasai penjajah terdahulu. Ia harus pulang demi nyawanya sendiri, dan aku tak bisa apa-apa selain merelakan kepergiannya. Dan setelah perpisahan kami, aku mendapati diriku tengah mengandung bakal anaknya.
Tak pelak, aku kelimpungan. Aku sama sekali tak tega untuk membunuh benih janinku, karena aku sama sekali tak membencinya. Sedangkan mempertahankannya, juga membahayakan bagi diriku sendiri. Ayahku pastilah murka jika mengetahui bahwa aku berbadan dua tanpa sosok suami. Apalagi kalau ia tahu bahwa lelaki yang menghamiliku adalah golongan penjajah.
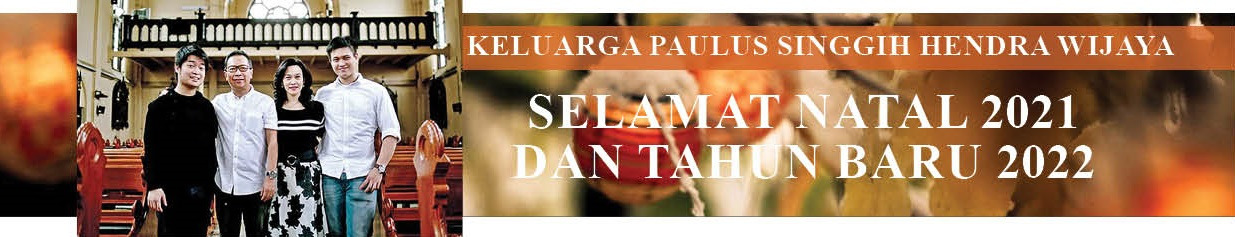 “Betapa terinjaknya harga diri kita sebagai sebuah bangsa. Harta benda kita telah dirampok bangsa penjajah itu, tetapi anak-anak perempuan kita malah sudi menjual harga dirinya kepada mereka,” kesal ayahku dahulu, setelah ia mendengar dari ibuku kalau seorang gadis tetangga kami telah menjadi pelacur demi menyambung hidup. “Kalau dia adalah anakku, sudah kubunuh dia!”
“Betapa terinjaknya harga diri kita sebagai sebuah bangsa. Harta benda kita telah dirampok bangsa penjajah itu, tetapi anak-anak perempuan kita malah sudi menjual harga dirinya kepada mereka,” kesal ayahku dahulu, setelah ia mendengar dari ibuku kalau seorang gadis tetangga kami telah menjadi pelacur demi menyambung hidup. “Kalau dia adalah anakku, sudah kubunuh dia!”
Namun beruntung. Aku menemukan jalan keluar untuk perkara yang kuhadapi. Di tengah kebingungan, aku berhasil menggaet hati seorang tentara pejuang yang cukup berumur. Tanpa menunggu waktu lama, kami lantas menikah di tengah rahasia yang terus kujaga. Hingga akhirnya, aku melahirkan anak lelakiku itu, dan sang pejuang hadir sebagai sosok ayah yang mencintainya.
Sungguh, karena keadaan yang bergolak, aku telah mengorbankan cintaku yang sejati. Aku harus berpisah dengan seseorang yang benar-benar kucintai, lantas menikah dengan seorang yang lain demi harga diri. Tetapi aku telah mengikhlaskan semua itu. Yang kuinginkan adalah sirnanya penjajahan dan peperangan di muka bumi ini, sehingga tidak ada lagi cinta yang bunuh diri.
Atas cita-cita itu, aku pun tak ingin menggoreskan sejarah kelam di benak anakku, apalagi menanamkan dendam di hatinya akibat pertikaian orang-orang terdahulu. Karena itu, saat ia mengungkapkan keinginannya untuk kuliah di negara asal ayah kandungnya, aku sama sekali tak melarang. Pun, saat ia meminta restu untuk menikahi seorang perempuan keturunan asli negara tersebut, aku pun tak mempermasalahkan.
 Dan akhirnya, di tengah renunganku atas sejarah bangsa dan kehidupan masa laluku yang getir, aku mendengar seruan salam dan ketukan dari balik daun pintu. Aku pun lekas membuka kuncian, hingga aku menemukan anakku dan keluarga kecilnya. Aku sontak memeluk mereka satu per satu, hingga aku merasakan kebahagiaan yang tiada tara atas cinta mereka yang melampaui rintangan bangsa dan negara.
Dan akhirnya, di tengah renunganku atas sejarah bangsa dan kehidupan masa laluku yang getir, aku mendengar seruan salam dan ketukan dari balik daun pintu. Aku pun lekas membuka kuncian, hingga aku menemukan anakku dan keluarga kecilnya. Aku sontak memeluk mereka satu per satu, hingga aku merasakan kebahagiaan yang tiada tara atas cinta mereka yang melampaui rintangan bangsa dan negara.
Untuk beberapa lama, kami duduk di sofa dan mengobrol tentang segala hal sepanjang perpisahan kami yang terakhir. Kami berbagi cerita dengan penuh kehangatan.
Sampai akhirnya, di sela-sela perbincangan itu, cucu perempuanku yang telah berumur tujuh tahun, tiba-tiba menunjuk dan mempertanyakan perihal sebuah potret yang menggantung di dinding, “Yang di foto itu siapa?” selidiknya, dengan pelafalan yang cukup baik, sebab ia memang bersekolah di sebuah sekolah untuk anak-anak sebangsaku yang menetap di negara seberang itu, sehingga ia belajar pula bahasa nasional kami.
Seketika, kami bertiga saling memandang, seolah-olah saling menyilakan untuk memberikan keterangan. Hingga akhirnya, aku mengambil alih dan menjawab, “Itu Kakekmu. Ayahnya ayahmu.”
Cucuku pun mengangguk-angguk paham.
“Kakekmu itu seorang veteran, Nak,” timpal anakku.
Sontak saja, cucuku jadi bertanya-tanya. “Memangnya, veteran itu apa, Ayah?”
Dengan penuh perhatian, anakku pun menjelaskan, “Veteran itu adalah orang yang memerdekakan bangsa ini. Ia adalah pejuang yang mengusir penjajah dari negara ini.”
Lagi-lagi, cucuku mempertanyakan rasa penasarannya, “Memangnya, siapa yang pernah menjajah negara ini, Ayah?”
Kami bertiga kembali saling memandang dan menyilakan untuk memberikan jawaban. Hingga akhirnya, anakku kembali menanggapi, “Penjajah negara ini dahulu adalah orang-orang yang dibutakan oleh harta benda. Mereka ingin mengambil kekayaan negara ini. Mereka ingin hidup senang dengan mengambil hak sesama manusia.”
Aku pun merasakan ketenteraman mendengar jawaban anakku itu.
“Nah, karena itu, kau jangan bersikap seperti para penjajah itu. Kau harus senantiasa bertindak sesuai hati nuranimu. Kalau kau tidak ingin dijahati, ya, kau jangan pula menjahati orang lain,” pesan menantuku, lantas membelai-belai rambut cucuku yang cantik itu.
Cucuku lantas mengangguk tegas.
Akhirnya, aku merasakan suasana yang begitu menenteramkan.***
Ramli Lahaping, Kelahiran Gandang Batu, Kabupaten Luwu. Berdomisili di Kota Makassar. Menulis blog (sarubanglahaping.blogspot.com). Telah menerbitkan cerpen di sejumlah media daring. Bisa dihubungi melalui Twitter (@ramli_eksepsi) atau Instagram (@ramlilahaping).



