
TEMPUSDEI.ID (10 APRIL 2021)
Oleh Dion Pare, Pemikir Sosial, Tinggal di Jakarta

Hari Selasa dini hari, 6 April lalu, Daniel Dhakidae meninggal dunia. Ilmuwan sosial dan ilmuwan politik yang diakui reputasinya ini meninggal karena serangan jantung. Banyak yang merasakan kehilangan seorang ilmuwan dan intelektual publik ini. Meninggalnya Daniel membuat semakin berkurangnya pemikir segenerasinya yang memiliki perhatian besar terhadap masalah-masalah negara, yang bersikap kritis terhadap kekuasaan, tetapi juga memberikan jalan-jalan yang perlu dilakukan.
Pengenalan saya dengan nama itu sudah berlangsung lama. Pada tahun 1981, melalui majalah Prisma di meja belajar kakak saya yang kuliah di Ende, pada waktu itu, nama itu masuk dalam ingatan saya. Setelah itu saya senantiasa membaca tulisan-tulisannya di Prisma dan Kompas. DI Jakarta, saya menghadiri seminar-seminar serta diskusi di mana Daniel tampil sebagai pembicara, moderator atau pun peserta biasa. Saya pun bertemu dengannya dalam kelompok yang lebih kecil, dalam rangka sebuah kegiatan tempat saya terlibat dan Daniel duduk sebagai pengarah acaranya. Dari kontak-kontak tersebut, saya memiliki kesan-kesan tentangnya. Catatan obituari kecil ini saya buat untuk mengenang berakhirnya kiprah hidupnya di dunia.
Hiperbolisme
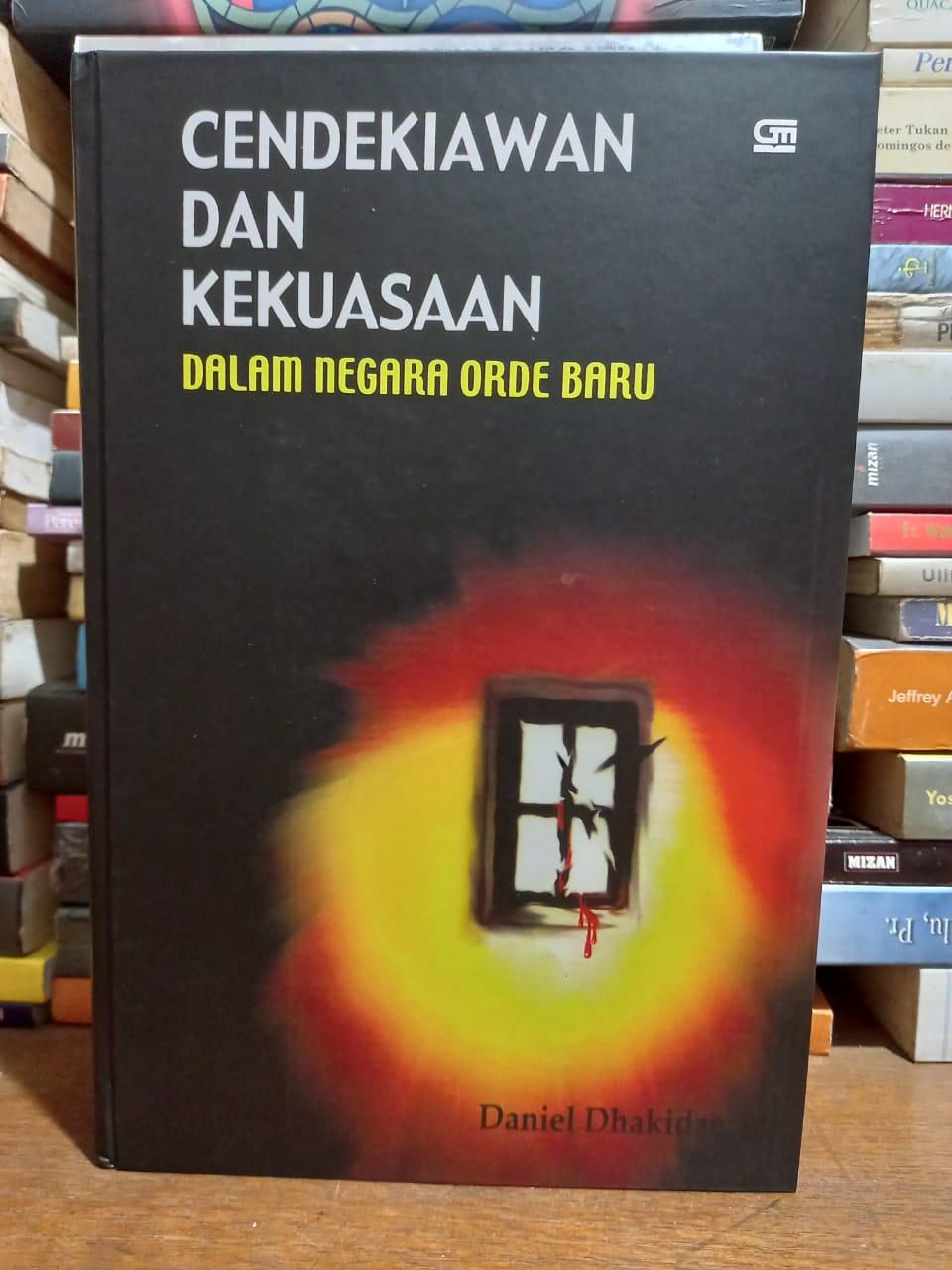
Ia selalu tampil dengan percaya diri. Gaya bahasanya tampak meledak-ledak dan menusuk. Hal itu bisa kita temukan dalam tulisan-tulisan dan presentasi lisannya. Dengan penuh keyakinan ia mengungkapkan pandangan atau pendapatnya. Hal itu mungkin disebabkan, seperti dikatakan oleh banyak pihak tentangnya, oleh keluasan pengetahuannya dan kemampuannya yang mumpuni dalam beberapa bahasa Eropa, seperti Latin, Jerman, Belanda, Inggris dan Prancis. Dengan kemampuan itu, ia bisa dengan lincah berselancar ke dalam pengetahuan yang ia miliki dengan bahasa-bahasa asing yang ia kuasai. Karena itu pula, ia bisa memakai gaya retorika yang memberi efek kuat dalam diskusi atau seminar.
Dalam seminar ekonomi Flores, pada tahun 2003, Daniel memperlihatkan gaya retoriknya yang khas. Ia sebetulnya hendak memberikan semangat atau motivasi tentang kemampuan masyarakat Flores untuk berkembang dan mengembangkan dirinya. Setelah menguraikan berbagai potensi alam dan sosial-budaya yang dimilikinya, Flores punya kans untuk berkembang.
Menurut Daniel, keadaan Flores pada tahun 1960-an, tidak jauh berbeda dari Jawa, bahkan dalam beberapa hal lebih maju berkat karya misi Gereja. Namun dalam 30 tahun belakangan ini, Flores ditidurkan atau dibiarkan tertidur. “Saat ini,” demikian katanya pada waktu itu, “setelah lama tertidur dan dibiarkan tertidur, Nipa Sawa ini sudah menggeliat.”
Sambil membetulkan posisi duduknya, dengan memandang para audiens dan menunggu reaksi mereka, dan dengan mulutnya yang lebih terbuka dan dagu dan bibir bawah ditarik agak keluar, ia melanjutkan bahwa itu semua tergantung pada masyarakat Flores sendiri, untuk membiarkan ular ini tertidur kembali atau bangun dan melibas semua yang membuatnya tidur panjang. Dan tepuk tangan pun menggemuruh. Itulah gaya yang sering ditampilkannya.
Nusa Nipa (imajinasi tentang ular sawah atau nipa sawah) adalah sebutan untuk Pulau Flores, dalam mitologi atau kepercayaan masyarakat Flores.
Ia pandai menggelola reaksi audiens dengan retorikanya yang hiperbolis. Hal ini terkait dengan gaya berbahasa yang secara sengaja memberi efek terhadap pendengar atau pembaca untuk memberikan reaksi atas apa yang disampaikannya. Efek itu bisa berupa diskusi yang dipertajam. Tetapi sering kali, gayanya itu menghasilkan reaksi yang membuat arena diskusi atau seminar menjadi gaduh dan diperlukan waktu untuk menjadi tenang kembali dan diskusi berlanjut. Kadang-kadang, orang lebih terpaku pada kegaduhan itu dan lupa dengan esensi yang hendak disampaikan.
Di sini saya mengangkat dua contoh retorik hiperbolis Daniel. Contoh pertama saya peroleh dari cerita seorang teman. Pada satu seminar di STF Driyarkara yang mengangkat tema Marxisme, Daniel juga hadir. Pembicaranya, salah satunya, adalah Romo Magnis. Seperti biasa, tanggapan tentang topik itu menjadi terlalu moralis. Mereka selalu menilai Marx sebagai anti agama dan anti agama itu tidak bermoral, maka Marxisme harus ditolak. Daniel pun meminta waktu untuk berbicara. “Kalau kita melihat reputasi yang dicapainya, Marx adalah seorang nabi.” Maka, riuhlah ruang seminar itu. Tentu saja, kata-kata Daniel itu memancing reaksi emosional dari para peserta yang rata-rata orang beriman kepada nabinya masing-masing. Romo Magnis pun hanya tersenyum-senyum saja.
Contoh kedua terjadi dalam seminar sekitar pemberian hadiah Magsaysay kepada Pramudya Ananta Toer, pada tahun 1995. Hadiah buat Pram itu membuat publik intelektual di Jakarta terbelah. Ada yang setuju, mengingat karya-karya yang ditulis oleh Pramudya. Sebagian lainnya tidak setuju dengan tuduhan bahwa Pram terlibat dalam peristiwa pembreidelan dan pembakar karya-karya sastra para lawannya pada tahun 1960-an. Untuk menjernihkannya, diadakanlah seminar di TIM. Saya ingat panelisnya pada waktu itu antara lain, Ikranegara, seorang dramawan dan Mochtar Pabotinggi, seorang ilmuwan politik dan juga penyair. Bertindak sebagai moderator adalah Ignas Kleden.
Setelah sejumlah orang menyampaikan pandangannya, giliran Daniel berbicara. Ia mulai dengan tesis. “Orang, yang meminta Pramudya meminta maaf setelah sekian tahun kehilangan hak-haknya, kehilangan kebebasannya, dan hidup secara tidak normal sebagai manusia, secara moral jorok.” Keriuhan pun mewarnai ruang diskusi. Daniel pun mengeritik seorang panelis yang mengatakan bahwa ia menandatangani penolakan hadiah Magsaysay kepada Pram dengan tangan gemetar.
Kata Daniel, seorang yang mengalami tremendum et fascinosum hanya dalam kondisi tidak punya pilihan lain, orang yang tidak memiliki cara lain, membiarkan hal itu terjadi pada dirinya, seperti manusia di hadapan Khaliknya. Kondisi itu tidak terdapat pada sang panelis. Panelis adalah orang yang bebas dan Pram bukanlah kekuatan yang menakutkan. Ia sudah lama ditindas dan karena itu menuntut Pram minta maaf, setelah penderitaan yang dialaminya, tidak bisa diterima.
Menggapai Kejernihan

Banyak pihak yang pernah bersentuhan dengan Daniel menyebutnya sebagai salah seorang intelektual par excellence. Orang semacam itu tergolong ke dalam begawan, disebut pula resi, atau mengutip Rendra: “mereka yang berumah di atas angin”. Mereka memberi isyarat, menabuh tanda, dan menggoreskan peta hidup masa depan.
Seperti disaksikan oleh banyak orang, Daniel adalah sedikit dari ilmuwan yang menjaga jarak terhadap kekuasaan, bersikap kritis, tetapi juga memberikan advis yang bermanfaat. Ia dekat dengan partai politik, dengan para politisi, tidak terjebak dalam permainan politik. Ia selalu sadar dengan posisinya.
Hal itu karena Daniel sangat peka dengan perspektif yang mungkin terjebak dalam kepentingan politik sesaat, yang lumrah bagi para politisi, tetapi sangat irritating bagi seorang begawan atau ilmuwan.
Salah satu metode yang dipakai oleh Daniel untuk menyingkapkan kesalahan berpikir umum itu adalah gayanya yang hiperbolis. Jika ia hendak menguji satu pandangan yang ditentangnya, ia mengungkapkan satu pandangan sebaliknya (metode dialektis), dengan gaya yang hiperbolis.
Hiperbolisme semacam itu membuat orang tersentak, dan mereka didorong untuk memeriksa kembali asumsi-asumsi atau pun fakta-fakta, dan segera menyadari bahwa asumsi atau data mereka palsu atau tidak cukup kuat. Tujuannya adalah agar orang tetap menjaga kewarasan, membuat lapangan pemikiran sosial politik tetap jernih dan kesimpulan untuk tindakan praktis bertolak dari dasar-dasar yang kukuh, dalam dan jernih.
Intinya, hiperbolismenya dimaksudkan untuk menjaga kedalaman dan kejernihan. Pesan itulah yang tertuang dalam buah pikirannya baik berupa buku-buku maupun artikel-artikelnya.
Selamat Jalan, Daniel Dhakidae, senior dan guru yang mengajar melalui tulisan-tulisan. Requiescat in Pace.



